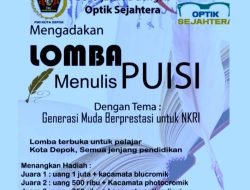5,364 total views, 6 views today
DELIK-HUKUM.ID ( JAKARTA ) —Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR RI mengakui, masih banyak kebocoran, penyelewengan dan korupsi di negeri ini.
“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini,” kata Prabowo dalam pidato tersebut.
Dari pidato tersebut, terlihat jelas orientasi Presiden Prabowo untuk mengurai akar persoalan korupsi yang selama ini mengakar secara sistemik di Indonesia. Secara implisit, amanat itu menegaskan urgensi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih, dengan menutup setiap celah kebocoran keuangan negara, memastikan perlindungan optimal terhadap uang rakyat, serta menindak tegas praktik-praktik koruptif baik di level mikro maupun makro, termasuk di kalangan swasta yang tidak menjunjung integritas.
Presiden Prabowo Subianto juga mengusung sejumlah gagasan yang visioner untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencananya membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Ide ini tentu menggugah imajinasi publik yaitu mengasingkan para pencuri uang rakyat di tempat terpencil demi menciptakan efek jera yang lebih besar.
Gagasan penjara di pulau terpencil memang memancing diskusi publik yang luas. Di satu sisi, itu menunjukkan keberpihakan terhadap ketegasan dalam menangani kejahatan korupsi. Dalam konteks di mana korupsi telah menjadi penyakit akut di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pendekatan simbolik semacam ini bisa menumbuhkan harapan baru.
Namun, perlu dicatat bahwa efek jera tidak hanya lahir dari tempat tahanan yang menyeramkan atau terisolasi, melainkan dari kepastian hukum, integritas proses hukum, dan keadilan yang tidak pandang bulu. Dalam banyak kasus, koruptor justru menikmati vonis ringan, remisi berlebihan, hingga fasilitas mewah di dalam tahanan. Tanpa pembenahan sistemik, membangun penjara di pulau terpencil bisa saja hanya menjadi kosmetik hukum.
Rangkap jabatan
Dalam kajian penyebab korupsi, salah satu rujukan penting adalah teori yang dikemukakan Robert Klitgaard dalam bukunya pada tahun 1988 yang berjudul: Controlling Corruption, Klitgaard merumuskan model konseptual yang menyatakan bahwa korupsi merupakan fungsi dari tiga variabel utama, yakni kekuasaan diskresioner (Discretionary Power), monopoli kewenangan (Monopoly of Power), dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (accountability).
Teori ini menegaskan bahwa korupsi akan cenderung terjadi ketika seorang aktor atau institusi memiliki tingkat diskresi yang tinggi dan menguasai monopoli kekuasaan/kewenangan, namun tidak diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban serta pengawasan yang memadai.
Dengan demikian, jika ditarik pada konteks penyelenggaraan negara, akar terbesar terjadinya korupsi terletak pada konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada individu atau kelompok tertentu tanpa adanya keseimbangan berupa mekanisme kontrol, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Kalau kita melihat dari realitas hari ini, teori yang dikemukakan Robert Klitgaard dalam bukunya: Controlling Corruption, konkretnya adalah bentuk rangkap jabatan yang hingga hari ini masih sering terjadi.
Jika dulu musuh bangsa adalah kolonialisme dan penjajahan oleh bangsa asing, kini musuh terbesar justru datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri salah satu contohnya adalah keserakahan elit yang memperkaya diri sambil membiarkan rakyat terjerat kemiskinan struktural. Salah satu bentuknya adalah praktik rangkap jabatan di kalangan pejabat, yang memperlebar jurang ketimpangan dan mempertahankan sistem yang menindas.
Di satu sisi masyarakatnya kesulitan mencari kerja, menjerit dari bawah, bahkan semakin membludaknya pengangguran terdidik. Di sisi lain, banyak pejabat yang merangkap di institusi-institusi negara hingga BUMN. Kalau kita ingin kembali ke esensi utama maruah jabatan publik, bahwa dalam suatu jabatan yang mengatasnamakan pemerintah, seharusnya ada tanggung jawab moral dan sakral di dalamnya.
Fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat BUMN, dan institusi publik lainnya sering kali berdalih pada optimalisasi kinerja, kebutuhan akan pengalaman, dan kapasitas individu tertentu.
Namun, dalam praktiknya, fenomena ini lebih banyak mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan konsentrasi sumber daya di tangan segelintir elit. Para pejabat yang merangkap jabatan memperoleh gaji dan fasilitas ganda, sementara masyarakat bawah berjuang mendapatkan pekerjaan pertama mereka.
Dalam realitas sosial dan politik Indonesia, fenomena rangkap jabatan di kalangan pejabat publik memang bukanlah sesuatu yang baru. Dari menteri yang sekaligus memegang posisi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, pejabat negara yang merangkap posisi strategis lainnya, hingga pejabat daerah yang merangkap dalam berbagai struktur kekuasaan lainnya. Praktik ini terus berlangsung tanpa kendali yang efektif. Ironisnya, ketika para elit menikmati berbagai fasilitas dan keuntungan dari rangkap jabatan, rakyat kecil justru harus menghadapi ‘rangkap penderitaan’, terjebak dalam kemiskinan struktural yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Inisiatif KPK
Regulasi mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif diatur secara tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Larangan ini memiliki rasionalitas yang kuat, yaitu untuk memastikan profesionalisme, menjaga fokus terhadap tugas pokok dan fungsi kementerian, sekaligus meminimalisasi risiko penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan. Lebih jauh, pengaturan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula terhadap wakil menteri. Dengan demikian, baik menteri maupun wakil menteri secara hukum tidak diperkenankan merangkap jabatan, sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga begitu visioner mendorong adanya Peraturan Presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD.
Maka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, MK telah menempatkan posisinya sebagai negative legislator dalam pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Artinya, secara yuridis terdapat landasan hukum untuk menginisiasi Perpres Larangan Rangkap Jabatan. Secara sosiologis merupakan harapan dari rakyat demi terselenggaranya keadilan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Secara filosofis, larangan rangkap jabatan melalui peraturan presiden diperlukan untuk menjamin integritas dan profesionalisme penyelenggara negara, mencegah konflik kepentingan yang dapat mereduksi kualitas kebijakan, memastikan distribusi kesempatan yang adil dalam ruang publik, serta menjadi instrumen pencegah akumulasi kekuasaan berlebihan yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Fenomena rangkap jabatan sesungguhnya merepresentasikan sebuah paradoks tata kelola pemerintahan yang menuntut penyelesaian segera. Kehadiran peraturan presiden yang secara tegas melarang praktik tersebut menjadi semakin mendesak, terutama dalam kerangka pencapaian visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sebagaimana secara konsisten ditegaskan dalam berbagai pidatonya.
Jabatan publik pada hakikatnya bukanlah ruang untuk kepentingan pribadi atau sekadar simbol status, melainkan sebuah amanah konstitusional dan moral yang bersifat sakral—ditujukan untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk negara, dan untuk kepentingan rakyat.
*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Alumni Kebangsaan Lemhannas RI, Penyuluh Anti- korupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK
( SYAFRIL/RED )